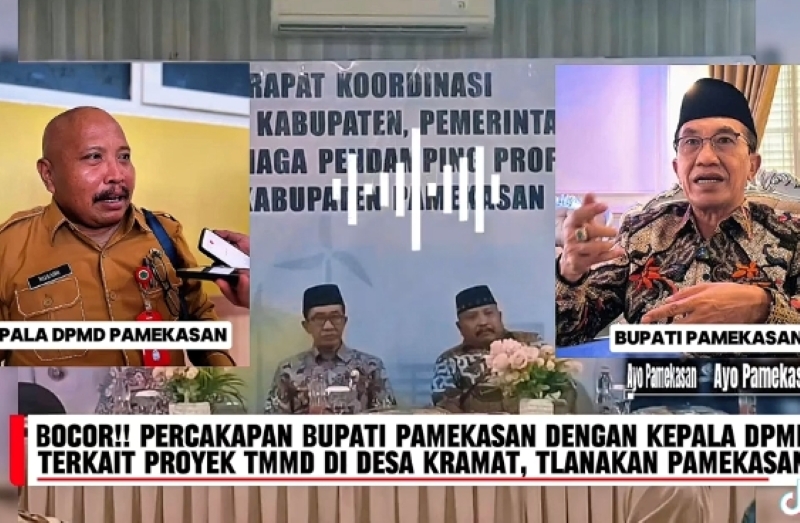Oleh : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. - Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Email: um_amana@pbs.uin-malang.ac.id
WAKAF adalah salah satu ajaran Islam yang memiliki komponen spiritual dan material. Sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umat (sebagai amal) atau untuk tujuan yang relevan dengan Islam disebut wakaf. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memasukkan konsep wakaf dari sudut pandang sejarah, fiqh, dan ekonomi makro.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ajaran Islam dalam menyediakan tempat ibadah. Ini juga merupakan salah satu ajaran yang ada sebelum Islam. Dari perspektif fiqh, para ulama fiqh menggunakan al-Quran, hadits, dan ijtihad untuk menjelaskan konsep wakaf dalam kitab-kitab mereka.
Konsep-konsep fikih terus berubah seiring perkembangan akal manusia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar konsep wakaf didasarkan pada ijtihad, yang dapat berubah tergantung pada tempat dan waktu. Dari perspektif ekonomi makro, harta wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan fasilitas masyarakat yang penting, seperti tempat ibadah, institusi pendidikan, dan pusat kesehatan. Fasilitas ini dianggap dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Wakaf berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk keperluan agama Islam (Teuku Iskandar, 2000: 1542). Tanah wakaf biasanya digunakan untuk membangun tempat ibadah (seperti masjid dan musola), institusi pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya.
Wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang memiliki komponen spiritual dan material. Wakaf memiliki banyak manfaat dan keuntungan, terutama dalam hal membantu orang miskin meningkatkan kesehatan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat dalam jangka panjang (Shalih Abdullah Kamil, 1993: 41).
Wakaf memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah unsur spiritual, karena wakaf adalah cabang ibadah yang memungkinkan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua adalah unsur material, karena wakaf dianggap sebagai upaya untuk mengubah harta benda menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan. Menurut pemahaman ini, wakaf memiliki tiga komponen penting dalam sistem ekonomi makro Islam: wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (Rate Of Interest), wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, dan wakaf mengandung elemen investasi dan tabungan. Baik itu digunakan sebagai modal pembangunan atau cara lain, harta wakaf juga dapat membantu ekonomi negara. Modal ini sangat membantu karena harta wakaf abadi.
Salah satu mekanisme redistribusi kekayaan adalah wakaf, yang memiliki elemen investasi dan tabungan. Baik itu digunakan sebagai modal pembangunan atau cara lain, harta wakaf juga dapat membantu ekonomi negara. Modal ini sangat membantu karena harta wakaf abadi. Modal untuk bisnis dapat berasal dari harta wakaf dan harta individu. Peruntukannya menentukan sebagian dari keuntungannya. Rumah wakaf juga bisa menjadi pendapatan.
Sistem Qard alHasan, yang berarti pinjaman kebajikan, memberikan wakaf kepada masyarakat. Dengan demikian, artikel ini akan membahas konsep wakaf dari perspektif fiqh, perspektif sejarah, dan perspektif ekonomi makro. Selain itu, akan dibahas peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat dan meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI).
Wakaf berasal dari kata Arab "Waqf", yang berarti "al-Habs". Ini adalah kata berbentuk masdar, yang secara umum berarti berdiri atau berhenti. Dalam kasus di mana istilah tersebut dikaitkan dengan harta benda, seperti tanah, hewan, atau lainnya, artinya adalah pembekuan hak milik untuk keuntungan tertentu (Ibnu Mandzur, 1990: 359).
Wakaf berarti sesuatu yang diberikan untuk kepentingan orang banyak (sebagai derma) atau untuk keperluan agama Islam. Wakaf juga berarti sementara (Teuku Iskandar, 2000: 1542). Dalam syariah Islam, wakaf didefinisikan sebagai pembekuan hak milik atas mata benda (al-Ain) untuk tujuan menyedekahkan kegunaan atau manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan umum (al-Jurjani, 2000: 328).
Namun, para ulama fiqh tidak setuju tentang definisi ini dalam kitab-kitab fiqh. Mereka berbeda tentang wakaf dalam hal kondisi riil benda (al-Ain) atas milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada seseorang yang diharapkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam, 1970: 203).
Dengan kata lain, wakaf tetap menjadi pemilik harta yang diwakafkan; perwakafan hanya terjadi ke atas keuntungan harta itu, tidak termasuk asetnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa wakif masih memiliki otoritas untuk memiliki harta yang diwakafkan.
Menurut Malikiyah, wakaf adalah memberikan manfaat harta yang dimiliki kepada orang yang berhak atas satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (al-Dusuqi, hlm. 75). Dalam definisi wakaf, wakaf hanya diberikan kepada orang atau tempat yang berhak. Orang yang berhak adalah orang miskin, anak yatim, dan orang tua yang sudah renta yang tidak memiliki pihak lain yang bertanggung jawab atas biaya.
Dalam definisi wakaf, wakaf hanya diberikan kepada orang atau tempat yang berhak. Orang miskin, anak yatim, dan orang tua yang sudah renta yang tidak memiliki orang lain yang menanggung biaya hidup mereka adalah salah satu orang yang berhak.
Sementara tempat yang layak menerima wakaf adalah tempat ibadah (seperti masjid atau musola), lembaga pendidikan, pusat kesehatan, panti asuhan, dan tempat lain yang diizinkan syara'. Kelompok Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bermanfaat dan kekal bendanya (al-Ain) dan memberikan hak pengelolaan wakif kepada tempat yang diizinkan (al-Syarbini, tt: 376).
Menurut kelompok ini, harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya dengan maksud, tidak rusak, dan memiliki manfaat jangka panjang, seperti tanah, rumah, hewan, dan alat perabotan (al-Syairazi, 1976: 575).
Di sisi lain, Hanabilah mengartikan wakaf dengan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan dari harta yang berupa tanah (Ibnu Qudamah, 1972: 185). Sesuai dengan definisi yang diberikan Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, wakaf Khairi (kebajikan) disyariatkan. Sebuah hadis mengatakan, "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah,
Saya membeli tanah Khaibar yang sangat berharga, dan saya belum pernah mendapatkan tanah yang lebih berharga. Apa yang harus saya lakukan? Jika Anda ingin, simpan pohonnya dan sedekahkan hasilnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Umar menyedekahkannya; harta itu tidak dapat dijual, dihadiahkan, atau diwariskan.
Dia menyedekahkannya kepada keluarga, fakir miskin, budak yang dibebaskan, orang yang berperang, musafir, dan tamu. Namun demikian, hasil tanah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang mengelolanya; mereka dapat memakannya sendiri atau memberi makan teman-teman mereka tanpa menjadikannya sumber kekayaan.Menurut hadis di atas, definisi wakaf lebih luas dan berkaitan dengan harta wakaf dan distribusinya (Syed Othman, 1987: 23).
Dengan membagikan sebagian harta Isam kepada orang lain, dia jelas menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan pemerataan terhadap umatnya, seperti yang ditunjukkan oleh maksud wakaf tersebut. Menurut beberapa definisi wakaf tersebut di atas, ajaran wakaf berarti bahwa pemilik asal memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan harta yang berkaitan untuk kepentingan pihak yang menerima wakaf. Dengan demikian, pemilik asal tidak lagi memiliki hak apa pun atas cara harta yang diwakafkan dapat digunakan. Selain itu, menurut madzhab Syafi'i, wakaf juga melibatkan pembekuan hak milik asal ke atas properti. Meskipun wakaf tidak melibatkan perpindahan milik kepada seseorang, harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu Allah SWT (al-Syairazi, 1876: 389). Dalam istilah manajemen, harta wakaf dikembalikan menjadi milik Negara (Mahmood).